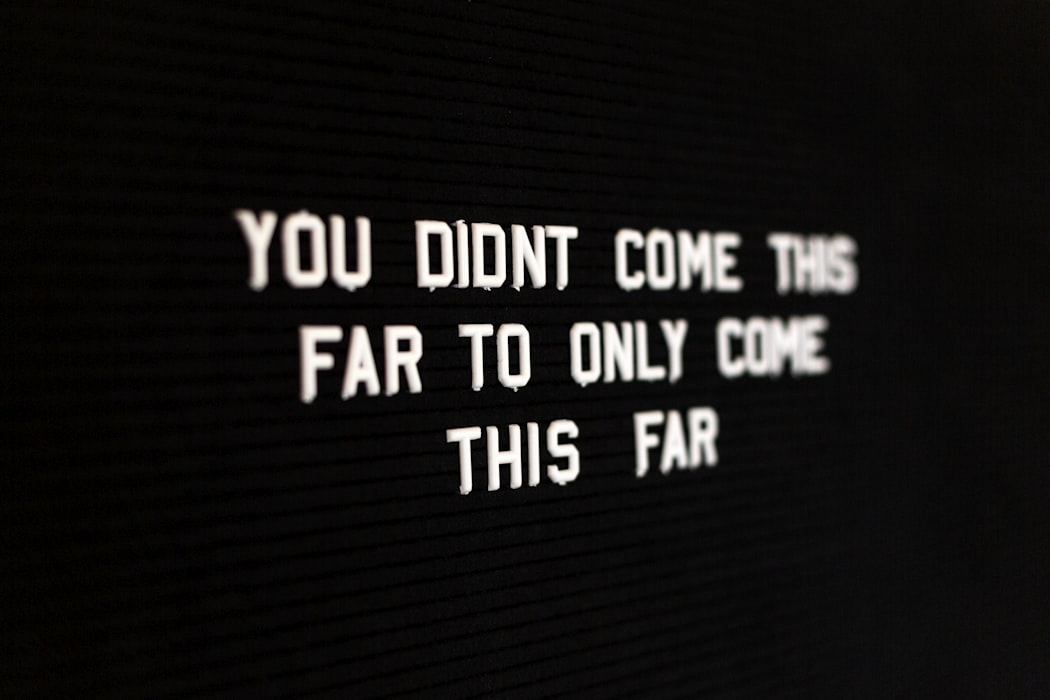Baru saja mau menulis ini, saya sudah struggling dengan rasa lelah + rasa malas + cuaca panas + mood swing. But this article, must, publish, lah. Like, tonight!
Jadi, topik penulisan hari ini adalah hal- hal apa saja yang membuat saya struggling dalam hidup. Sama dengan manusia lainnya, ya banyak. Sedikit berbeda dengan manusia lainnya, saya mempunyai mental health issue.
Tapi, mari kita bicarakan hal itu lain kali saja, kali ini saya sedang ingin berbicara mengenai bagaimana minimalism membantu perjuangan hidup saya. Dari awalnya hanyalah manusia yang mengikuti arus dan mengikuti social norms seperti berpakaian rapi dan seringnya baru, budaya shopping, mengikuti trend secara umum deh, intinya.
Namun begitu saya benar- benar memahami idea of minimalism, ternyata saya hanya mengikuti semua itu untuk membuat orang lain terkesan dan membangun image pribadi yang sebenarnya saya tidak perlu. Saya tidak perlu image yang fancy atau tampak sukses, padahal saya tidak ada kemampuan untuk semua itu.
Lagipula, kenapa, sih saya harus menyenangkan orang lain? Selalu tampak presentable di depan mereka setiap saat? Bahkan sejujurnya saya tidak peduli siapa pun mereka dan tidak butuh validasi apapun. Apa yang mau divalidasi juga, kan? Ahahaha memangnya saya barcode, harus validasi?
Mungkin pembaca yang sering nyasar ke Ann Solo sudah paham dengan konsep ini, yang sering dipetik dari quote film Fight Club. Atau dari orang- orang sukses lainnya. Intinya sama, jangan jadi people pleaser dan memberi image seolah sempurna padahal Anda sendiri tidak mampu untuk itu. Simple, is it?
Kenyataannya sih, tidak.
Okay, balik lagi, jadi ini adalah salah satu perjuangan umum dalam hidup bagi semua manusia, is to be accepted. Diterima dengan apapun caranya itu. Istilahnya, dapat tanda check, gitu.
Minimalism masuk sebagai penetral perasaan itu, karena menjadi seorang minimalist adalah berani mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri sehingga menyingkirkan rasa minta diakui oleh orang lain (wuih, cerdas sekali Ann Solo ini, ya, silahkan di quote tapi tag saya, ya).
Seorang minimalist cerdik dengan penataan uang dan budget mereka, tidak membeli sesuatu hanya karena menurutkan emosi dan gengsi sesaat. Tidak mudah tergiur diskon dan cara pemasaran yang sebetulnya tidak betul- betul tepat. Buy 1 get 1 dengan jumlah segini, padahal beli 1 saja sudah cukup karena bisa jadi barang tersebut berpotensi tidak sehebat yang kita pikirkan sebelumnya.
Takut ketinggalan diskon lagi kalau tidak membelinya sekarang? Ya, sama. Saya juga sering berpikiran demikian. Terlalu sering.
Ternyata oh ternyata, diskon dan penawaran selalu akan datang silih berganti. Mungkin tidak pada barang yang sama minggu depan, tapi sama seperti setiap siklus, cepat atau lambat penawaran yang sama akan terulang kembali.
Ini sudah saya buktikan sendiri. Ketahuan ya, kalau saya kebanyakan waktu luang sehingga saya iseng melihat apa saja penawaran dan diskon dimana- mana. Maklum, sebelum memutuskan menjadi minimalist, saya cukup senang shopping dan hoarder at some point meski keuangan morat- marit. Dark times sungguh saat itu.
Now I’m older and wiser. Tidak juga, tua itu jelas, bijaksana itu rasanya suatu anugerah kalau bisa mendapatkannya. Saya lebih cenderung menganalisa banyak hal dalam hidup (saya jadi ingin kerja jadi data analyst, deh) dan menarik banyak study case hingga bisa juga dibilang, kesimpulan dari padanya. Yaitu, saya jadi yakin, kalau kita tidak selalu membutuhkan apa yang ditawarkan brand kepada kita.
Saya tidak perlu berapa helai blazer hanya karena itu sedang trend di Instagram dan banyak influencer Korea terlihat keren memakainya. Saya tidak perlu harus mencoba semua mereka skincare dan makeup yang setiap jam muncul bagai jamur sehabis hujan. Saya tidak butuh perasaan sedih dan depresi karena ketinggalan trend terbaru sedangkan rekan sesama beauty blogger/influencer sudah pernah memakai produk dari brand yang sedang hype tersebut.
Hype sendiri adalah hal gila. Hype, trend, hashtag, viral, dan sejenisnya adalah hal- hal yang membuat kehidupan zaman ini terasa sulit dan membelenggu. Sama seperti pernikahan dua orang egois yang tidak mau mengakui kesalahan dan sebaiknya bercerai saja daripada membuat dunia anak mereka hancur, hype dan kawan- kawan adalah rantai di kaki.
Berapa kali saya bertanya dan ditanyakan, “Kamu tidak tahu ini-itu? Masa sih, ini-itu siapa ini- siapa itu kamu tidak tahu?”.
Hello.
Ada banyak ini-itu dan siapa ini- siapa itu yang tiba- tiba nongol, tentu saja saya tidak tahu semuanya. Bahkan apa yang trend di zaman saya masih muda saja, saya tidak ingat semua. Lalu apakah itu penting?
Tentu saja tidak.
Hanya saja, kalau kamu tidak tahu trend dkk, ya, kamu biasanya akan mengalami sindrom of FOMO dan no longer SWAG coz you’re not DOPE.
Saya melihat langsung sindrom FOMO alias Fear Of Missing Out ini pada banyak orang di sekeliling saya. Sayangnya mereka tidak mengenal FOMO dan bahkan tidak tahu FOMO itu ada padahal sudah hype lama. Now, who’s the DOPE one here, hey?
FOMO membuat orang- orang anxious, cemas kalau mereka tidak mengetahui suatu hal dan merasa tersisihkan. Ini cenderung akan memicu atau triggering ras su’udzon yang berujung pada BAPER. Dari sini, saya selalu menjadi target dan korban dari orang- orang FOMO yang su’udzon dan baper ini. Bahkan hingga sampai membuat saya terancam dan berpikir keras, WHAT’S WRONG WITH YOU PEOPLE?!
Namanya mereka juga tidak tahu apalagi sadar apa yang telah mereka lakukan, mereka terus akan merasa benar. Hingga, mau tidak mau, secara naluriah pula, saya akan membalikkan prasangka yang direfleksikan dari perlakuan mereka pada saya.
Bak kata masyarakat TikTok: IRI BILANG, BOSS!
Iri adalah perasaan wajar dari manusia, baik kadar rendah maupun kadar busuk hati yang berujung pada banyak variasi dalam melampiaskannya. Meski saya pemalas kalau dalam hal iri hati dan respon normal saya biasanya ; ya, rezekinya, kenapa saya harus pusing?
Tetapi, saya juga terkadang iri. Kenapa mereka lebih keren, wajahnya simetris, sukses, kaya, bahagia, punya pasangan yang ‘kelihatannya manis’, bisa liburan kesana kemari, bla bla bla. Itu semua normal terlebih dengan exposure dari media sosial saat ini yang selalu ajang pamer legal dengan over exposure.
Rasa ingin mendapatkan hal yang sama tersebut membuat saya anxious, bahkan saya juga berpikir saya berhak mendapatkan semua kebahagian tersebut. Iya, saya memang berhak mendapatkan kebahagian, tetapi kebahagian yang dibutuhkan setiap orang berbeda porsi, situasi dan kondisinya. Ya, saya akan bahagia liburan kesana-sini nanti jika saya ada rezeki dan virus sudah reda. Ya, saya mungkin akan bebas masalah finansial kalau saya belajar berinvestasi pada hal yang tepat. Macam- macam kebahagian buat saya, kurang lebih sama dengan orang lain dengan bumbu khas berbeda.
Mood swing membuat rasa iri dan tidak saya terombang- ambing mengikuti mood saya yang swing ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ditambah depresi dan penyakit mental yang saya derita dari dulu, tidak mudah untuk berhadapan dengan rasa iri dan mengatasinya dengan logika. I like to reason with myself.
Walau di agama rasa iri itu sangat dilarang keras, tapi entah kenapa, rasa iri itu sebenarnya cukup sehat dengan kadar yang cukup. Saya adalah contoh orang yang tidak cenderung lempeng tidak menjadikan rasa iri sebagai motor dalam hidup sehingga saya tidak punya ambisi. Mungkin saya punya cita- cita, tapi saya tidak punya ambisi yang kuat untuk menggerakkan diri saya.
Punya rasa iri yang tepat sebenarnya baik, itu akan memacu diri kita. Tapi kalau salah dosis, itu bisa menghancurkan hingga membusuk yang nantinya muncul istilah busuk hati (pandai sekali saya, berkata- kata, ya?).
Seorang dengan pribadi lempeng seperti saya, tahu apa, sih? Apapun rezeki orang lain, saya yakin itu adalah hadiah kerja keras mereka, doa tanpa henti, keberuntungan, bantuan dari orang lain, dll. Kemudian, kenapa saya harus iri dengan mereka? Walau dia adik saya sekalipun, tentu saja jalan hidup berbeda. Lalu kenapa harus repot- repot iri?
Benar, saya malas sekali merasa iri. Lelah begitu, karena hampir seringnya itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jad, kenapa repot- repot buang waktu? Mending bawa webtoon dan baca e-book ahahaha
Logis, bukan?
Lha, iya memang logis.
Begitu, saya tetap mempunyai anxiety akan ekspektasi pada diri saya sendiri. Umur sekarang ini, saya harusnya sudah berkeluarga dengan 3 anak dan suami cakep, tajir bin bucin pada saya. Siapa yang membuat keharusan ini? Kebiasaan dari masyarakat bumi.
Faktanya, saya melawan arus aturan sosial. Tidak sengaja melawan arus aturan sosial karena saya hanya menjalankan hidup selayaknya orang lain, tetapi memang saya belum menapaki ‘jenjang’ kehidupan seperti orang lain. Jalan saya berbeda, instead of taking stairs straight up, saya malah berputar, menggelinding, lompat- lompat apapun itu.
Jalan hidup tidak sama dan yang menentukan itu ya, Tuhan. Senangnya, manusia playing God. Menambah deretan anxiety saya.
Mulai dari saya harus memenuhi kuota shopping dan berpakaian mengikuti tren, kulit glowing dengan ribuan produk dan merek, bersikap dengan rules tertentu, menjadi manusia, perempuan, anak, saudari, tante, teman dll, membuat saya anxious.
Saya tidak bisa memenuhi itu semua karena betapa pun saya mencobanya dengan keras, tidak semua orang akan menyukainya. Daripada saya harus memaksimalkan apa yang tidak akan pernah bisa saya penuhi, lebih baik saya beralih menjadi minimalist.
Dalam minimalism, selain mengurangi semua hal yang terlalu sesak untuk ditinggali baik secara harafiah maupun kiasan, cara hidup sederhana ini membuat pikiran dan tekanan sosial saya menjadi lebih bearble, tidak mudah dilalui tapi dapat dilakukan.
Kebendaan dan validasi tidak lagi membuat saya cemas dan literally sweating, saya bisa merelakan banyak benda yang mungkin dulu punya nilai sentimentil (well, I don’t have much problem letting the stuff go, it’ll only chained me, I hate to be chained down), melepaskan masa lalu yang sebenarnya cukup buram untuk diingat tapi selalu di romanticize, hingga merelakan orang- orang yang telah membawa kenangan buruk pada saya.
Mengikuti jalur minimalism membuat saya melihat hal dari sudut pandang berbeda, bahkan saya keluar dari kotak untuk melihatnya dari semua sudut jika memungkinkan. I mean, saya mengakui saya kecanduan menghabiskan waktu yang terbuang sia- sia dalam hidup, namun, saya juga harus mengakui bahwa saya menderita penyakit mental yang parah saat itu. Tidak perduli betapa saya ingin waktu itu kembali, saya sakit dan itu adalah salah satu waktu terberat saya dalam hidup ini.
Minimalism membuat saya paham akan banyak konsep dalam hidup, hingga saya pun ‘ngeh’, bahkan nabi kami, Muhammad SAW juga adalah seorang minimalist sejati. Beliau bisa memiliki bulan, bintang, gunung, emas, you name it, tapi beliau tidak memerlukan itu semua karena pada akhirnya itu hanyalah rantai dan tidak relevan.
Jangan munafik juga, kita memerlukan uang untuk hidup, oh, I tell you I love money like everyone does. In fact, saya kepingin punya tabungan 21 Miliar dollar dan properti disana- sini jadi saya bisa berbagi dengan orang- orang terkasih dan menolong mereka yang membutuhkannya. Bahkan saya akan merasa terlindungi dengan itu semua; MONEY.
Sampai pada suatu titik, ya, kita tentu merasa nyaman kalau kita mempunyai dana yang bisa menopang hidup kita dalam keadaan darurat sekalipun. The point is; kaya seperti Zuckerberg tapi terlihat ‘miskin’ juga seperti Zuckerberg. Eh tidak ding, tidak harus sekaya itu karena pasti bayar pajaknya sulit, sudah tahu kan, saya orangnya pemalas apalagi kalau harus mengurus pajak ini-itu.
Maksud saya adalah punya uang lebih itu bagus, like you actually needs 10 but you got 15. Ini bagus karena akan membuat safety nets. Tapi jika berlebihan dengan tidak adanya kemampuan mengolah dan cenderung tidak dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan dari banyak uang, money only caused you anxiety.
Ya, seperti orang rich kids, rich people on Instagram, punya uang berarti you flaunt them to yo haters. You show them your LV toilet seat. Saya tidak butuh yang seperti itu tapi tidak yang seperti Zuckerberg juga. My point is, kalau saya sekaya itu, saya akan benar- benar menghilang dari publik dan menikmati hidup setenang mungkin jauh dari keramaian.
Balik ke realita, apa yang membuat saya anxious adalah ketidakpastian dan masa depan. Seorang minimalist tidak membeli hanya karena just in case yang berarti prediksi masa depan cenderung tidak akan terjadi karena pembelian tersebut tidak berpotensi cukup baik di masa depan. Ini sudah terjadi kepada saya dalam hal memberi barang sebagai ‘stok’.
Masa depan adalah hal yang menakutkan and I need a grasp of it yang mana itu mustahil. Jadinya saya mengikuti beberapa petuah logis (saya benci petuah yang tidak logis) dari para pendahulu minimalist yakni; menabung itu penting, investasi jika memungkinkan, selalu merasa bersyukur dan berkecukupan, bahkan apa yang saya punya saat ini sebenarnya sudah cukup.
Meski saya masih takut akan masa depan yang blur di depan saya, paling tidak dengan menjadi minimalist, perasaan anxious saya mendapatkan reason yang masuk akal dan mengurangi struggling akan hal- hal yang sebenarnya tidak penting. Anyway, who needs 10 different serums like heck you can lather them in your face at the same time?